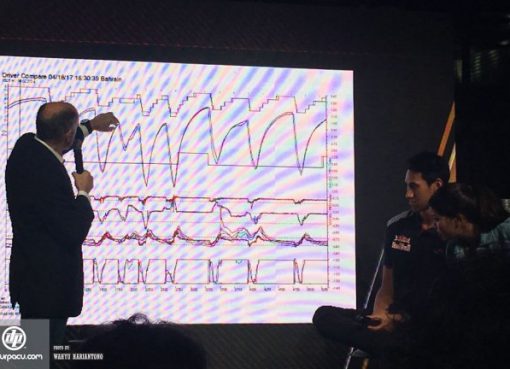Setiap melihat bendera kuning kecil, perasaan Munir jadi tak menentu dan dadanya deg-degan. Ia membayangkan wajah kaku, diselimuti kain putih atau batik. Orang-orang mengelilinginya, tetangga berdatangan dan duduk di kursi-kursi yang disiapkan di halaman atau di gang-gang sempit di kawasan bendera kuning itu ditancapkan.
Bendera kuning itu tanda ada kematian. Munir mengerti, bendera tanda kematian itu berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Di daerah Jawa Timur, ada yang memasang bendera merah dan di Sumatera menggunakan bendera hijau. Kayak bendera partai saja, katanya. Tapi di Jakarta, orang menggunakan bendera kuning sebagai tanda kematian.
Bukan hanya bendera. Mendengar suara sirine mobil pun, ia langsung seperti terpacak di tempatnya. Mobil putih ambulans yang membunyikan sirine itu, pasti membawa orang mati atau sedang sakit parah, bisiknya dalam hati.
Terkadang bila ia pulang kerja, di ujung gang yang mengarah ke kediamannya terpasang bendera kuning. Ia berjalan perlahan, sembari berdesis, “Siapa lagi yang meninggal?”
Munir amat rajin mengikuti penyembahyangan dan penguburan orang meninggal. Ketika jenazah diusung kemudian dimasukkan ke dalam lubang di pemakaman, ia mengamatinya dengan seksama. Ia selalu meremang. Ia membayang-bayangkan kemana orang itu pergi. Ia menghubung-hubungkannya dengan isi kitab suci atau ucapan para ustad, yang mengatakan manusia itu akan pergi ke alam lan. Alam yang lebih langgeng bahkan alam abadi.
Ia membaca buku yang menceritakan tentang kematian. Bila orang itu tidak banyak dosanya, maka rohnya akan diusung malaikat di atas kain hijau yang harum. Ia akan naik ke angkasa, entah ke alam mana, dan mulai ditanyai tentang perbuatannya di dunia. Bila orang itu banyak dosanya, ia mulai ditanyai dan dihukum saat orang-orang yang mengantarnya ke kuburan baru meninggalkannya tujuh langkah.
“Luar biasa ngerinya,” pikirnya, “Apakah kita nanti masih bisa menyaksikan jasad kita dikerubungi cacing dan binatang tanah lainnya.”
“Manusia tidak bisa lagi menipu bila ditanyai malaikat. Karena katanya seluruh anggota tubuh kita yang akan menjawab berbagai pertanyaan itu. Seluruh tubuh kita yang berbuat sesuai fungsinya selama hidup. Orang yang korupsi itu, bila ditanya, pasti yang menjawab adalah otaknya, hatinya dan tangannya yang menerima uang haram itu,” Munir semakin membayangkan kehidupan mendatang.
Munir teringat berbagai peristiwa yang pernah dialami dan diperbuatnya. Kilasan-kilasan peristiwa itu seperti diputar ulang. File-file kejadian masa lalu seperti berebut masuk drive komputer di otaknya.
Ia teringat masa kecilnya di kampung halaman, ketika mencuri uang orang tuanya, ketika mengambil tanpa ijin buah mangga dan tebu tetangganya. Ketika baru megninjakkan kaki di Ibukota, ia nganggur karena susah sekali mendapatkan pekerjaan yang layak dan halal. Ia numpang di rumah kontrakan temannya dan terbayang berbagai kisah mesum yang dilihatnya.
“Itu kan dulu. Tapi kan semua tercatat di buku malaikat. Ah, bagaimana aku meminta mereka untuk menghapusnya. Mereka tidak punya nafsu, tidak memiliki keinginan apa pun, lagi pula bagaimana menyogok makhluk yang tidak kelihatan,” pikir Munir.
Ia paham betul, untuk menghilangkan dosa-dosa masa lalu, ia harus bertobat kepada Yang Maha Kuasa. Setiap berdia usai solat, ia memang minta ampun, tapi ia merasakan Tuhan tidak mendengar permintaannya. Ia dihantui dosa masa lalu. Pikiran itu selalu menyergap setiap saat, apalagi bila malam hari ia tidak bisa tidur. Biasanya ia merasa tenang bila sudah solat malam hari, tapi lagi-lagi file masa lalu itu tidak kunjung sirna dari pikirannya.
Ia teringat ketika menjual kertas-kertas bekas di kantornya tanpa sepengetahuan atasannya. Ketika pulang kerja sebelum waktu kerja usai. Ketika mengatakan kepada tetangga, bahkan familinya, bahwa ia tidak punya uang ketika mereka membutuhkannya dan ingin meminjamnya. Berbagai dosa besar dan dosa kecil selalu dengan semrawut melintas di benaknya.
Ia tak mampu membayangkan jawaban pertanggungjawaban orang-orang yang korupsi bermiliaran rupiah. Kasus “bulog-Gate” Akbar Tanjung dan Gus Dur itu atau kasus Tommy Soeharto yang macam-macam itu, entah siapa yang benar, pikirnya. Kayaknya uang milyaran rupiah itu digunakan untuk partai, bukan untuk diri pribadi. Apakah mereka bersalah? Tapi itu kan uang rakyat. Ah, Munir tak kuasa memikirkannya, Pengadilan yang benar adalah di hadapan Yang Maha Mulia Sang Pencipta, bukan persidangan di Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan atau di Pekan Raya Jakarta itu, pikirnya.
Munir jadi pendiam belakangan ini. Istri serta teman-temannya di kantor heran. Munir selalu seperti bertafakkur dalam mulutnya komat-kamit.
oOo
Tubuh Munir bergetar, keringatnya mengucur dan langkahnya satu-satu, ketika petang iti ia melihat bendera kuning di ujung gang memasuki rumahnya.
Ketika melihat rumahnya dari kejauhan, banyak orang berkumpul, dadanya semakin berdegup, matanya mendelik, kakinya gontai, keringat mengalir dari kakinya seperti dihisap dibumi. Ia masuki ke dalam rumahnya, orang-orang seperti tak memperhatikannya, dan ternyata…ia melihat dirinya sendiri berbaring di ruang depan, ditutupi sehelai kain batik.
Istri dan anak-anaknya menangis mengelilinginya. Saudara-saudaranya yang lain membaca kitab suci. Orang silih berganti datang dan menyalami keluarganya. Istrinya bahkan beberapa kali semaput.
Ia heran, kok orang-orang berdatangan dan keluarganya menangis? Toh saya masih ada, tapi kok berbaring kaku di atas ranjang kecil itu. Ia mendatangi anaknya dan membelai kepalanya, tapi ia seperti menangkap asap. Suaranya pun tidak ada yang mendengar, padahal ia sudah berusaha berteriak sekuat mungkin.
“Selamat datang di kelanjutan hidupmu berikutnya. Kami datang menjemputmu,” ia mendengar suara serak-serak basah. Munir menoleh ke pojok rumah, ada dua orang berpakaian putih hingga ke kaki sedang menunduk, ia tidak bisa melihat wajah mereka.
“Kamu tidak perlu membawa apa-apa. Yang kamu perlukan menyiapkan jawaban atas semua yang sudah kami tulis,” kata orang itu. Di tangan salah seorang, ada buku amat tebal. Tubuh kedua orang itu seperti bersinar dan mengeluarkan aroma harum.
“Kenapa terlalu cepat? Aku belum siap. Aku masih harus mengasuh anak-anakku. Aku masih ingin berbuat banyak kebaikan untuk menebus keburukanku di masa lalu. Tolonglah aku,” ujar Munir. Tapi kedua orang itu hanya menjawab, “Kami Cuma menjalankan tugas kami.”
“Tolonglah teman. Beri aku waktu beberapa waktu lagi. Sekitar dua atau tiga tahun lagi kek,” Munir terbata-bata. “Tidak ada waktu terjadwal yang bisa dimajukan atau dimundurkan,” jawaban orang yang menunduk itu.
“Kemana aku akan kalian bawa?” tanya Munir.
“Kau akan memasuki alam kubur. Kemudian kea lam barzah untuk mengadilimu. Dari situ baru ketahuan apakah kau dimasukkan ke surga atau neraka,” kata orang atau makhluk itu.
“Tak bisakah kau beritahu sekarang apakah aku masuk surga atau neraka?”
“Tidak bisa. Semua harus melewati perjalanan waktu. Proses di duniamu sama dengan proses di dunia setelahnya. Ada perjalanan waktu. Ada proses. Bahkan bila kau masuk neraka jahanam pun, kelak kau akan naik setingkat demi setingkat sampai akhirnya dilempar kesurga jannatun’naim. Makanya sabarlah. Biar orang-orang itu membersihkan fisikmu sebelum kau dimasukkan ke dalam tanah,” bunyi jawaban.
“Bolehkan aku meninggalkan pesan untuk istri dan anakku?”
“Pesanmu sudah jelas. Ialah perbuatanmu masa lalu kepada mereka. Itulah pesan yang paling berarti bagi mereka dan lingkunganmu,” jawabannya.
“Kenapa kau tak memberitakukan lebih dulu bahwa aku akan kau jemput?”
“Itu sudah aturan dari sononya.”
“Oh, kenapa aku lalai selama ini.”
“Sesal kemudian tak ada artinya.”
Munir merasakan tubuhnya semakin menggigil. Perasaannya tak karuan. Ketakutan luar biasa memasuki alam baru dan kebahagiaan karena akan bertemu dengan Penciptanya bercampur baur. Ia menggeliat seperti tak hentinya, diiringi teriakan keras. Tubuhnya seperti digoyang-goyang. Dipukul-pukul. Ia terhentak. Ia mendengar suara orang, “Munir, sudah masuk waktu Ashar. Kok kamu teriak-teriakkan sih. Makanya jangan sembarang tidur.”
Munir terduduk menyeka keringatnya. Ia melihat jam di dinding mushola di kantornya, pukul 15:10 WIB. Ia mencubit-cubit lengannya yang bersimpah keringat. Ia membayangkan bendera kuning terpencak di ujung lorong-lorong di mana saja.
***
Jakarta, 2002. (dari kumpulan cerpen In Memoriam X karya A.R. Loebis)