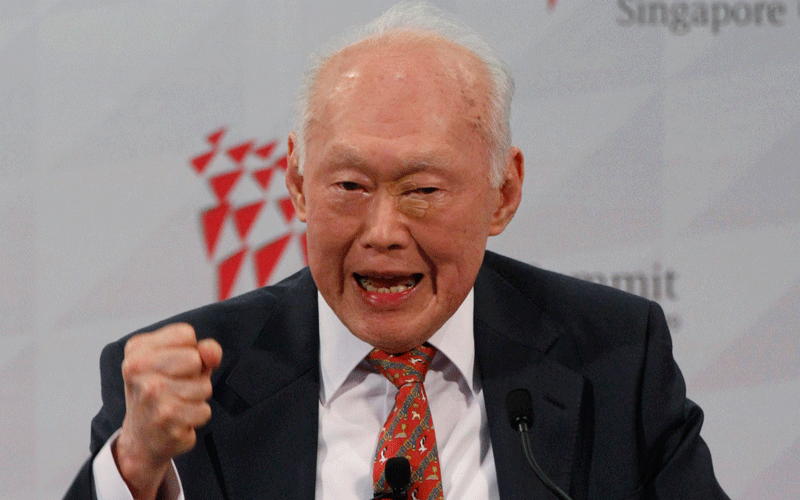MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) – Satu lagi tokoh pers meninggal dunia setelah Tarman Azzam yang berpulang Jumat 8 September 2016, yaitu Siti Latifah Herawati Diah yang berpulang di usia 99 tahun di Rumah Sakit Medistra Jakarta, juga pada Jumat.
Jenazahnya akan dimakamkan selepas Shalat Jumat di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, berdampingan dengan makam sang suami, Burhanuddin Muhammad Diah (1917 — 1996).
Siti Latifah Herawati Diah lahir di Tanjung Pandan, Belitung, 1917, adalah anak ketiga dari antara empat bersaudara.
Ibunya Siti Alimah binti Djojodikromo dan ayah Raden Latip. R. Latip adalah lulusan sekolah dokter Stovia tahun 1908, membuka praktek di pulau tetangga Bangka itu sebagai ahli medis sebuah perusahaan tambang timah Belanda.
Saat penyusunan cetakan kedua Ensiklopedia Pers Indonesia (EPI) terbitan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada 2010, Herawati pernah menyatakan, tanpa melepas pendidikan agama Islam dan tradisi, Ibu Alimah mendorong anak-anaknya untuk merangkul gaya hidup Barat yang bertujuan mengimbangi kaum penjajah Belanda.
Khusus Herawati mula-mula dikirim ke sekolah di Jepang. Berlanjut ke Amerika Serikat, di mana pada tahun 1941 dia menjadi wanita pertama Indonesia yang berhasil meraih gelar sarjana dari luar negeri. Ia menjalani studi di Barnard College, Universitas Columbia, New York, AS. Pada musim panas ia belajar jurnalistik di Universitas Berkeley, California.
Mengapa belajar ke Amerika dan bukan Eropa, karena ibu dari lingkungan priyayi tersebut telah memutuskan bahwa Herawati harus menuntut ilmu ke “negara yang tidak punya jajahan.”
Lima tahun selesai studi, kembali ke Indonesia. Jepang menyerbu ke selatan dan menggulingkan semua pemerintahan jajahan Eropa di Asia Tenggara, demikian riwayat hidup wartawan perempuan itu seperti dilansir antaranews.
Ternyata, latar pendidikan Amerika yang dimilikinya sangat diperlukan segera guna menghadapi berbagai peristiwa genting yang melanda Indonesia. Maka, Herawati tergiring untuk menjalankan tugas-tugas jurnalisme.
Dia setengah dipaksa bekerja di stasiun radio penguasa militer Jepang yang membutuhkan penyiar berbahasa Inggris untuk keperluan propagandanya.
Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu dan Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dia sempat menjadi sekretaris pribadi menteri luar negeri pertama republik, Mr. Achmad Soebardjo, yang kebetulan pamannya.
Lalu, Herawati membantu suaminya menerbitkan koran pro-Indonesia Merdeka karena Republik Indonesia, satu pemain baru dalam arena politik internasional yang belum teruji, membutuhkan media komunikasi untuk melawan Belanda dan Sekutu yang mengotot ingin memulihkan rezim Hindia Belanda. Maka beredarlah harian Merdeka sejak 1 Oktober 1945.
Sejak bulan Oktober 1954, dia memimpin harian baru berbahasa Inggris, Indonesian Observer, untuk mengkampanyekan aspirasi kemerdekaan RI dan negara-negara masih terjajah, yang makin menggelora sejak penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 di Bandung.
Apakah jurnalisme itu di mata Herawati Diah? Menurut dia, jurnalisme paling tidak menuntut kecintaan pada pekerjaan dan membutuhkan pengindahan terhadap hati nurani.
“Hati nurani adalah penyuluh dari pekerjaan dan sukses wartawan, justeru karena inti dari profesi ini adalah pengabdian kepada kepentingan umum. Inilah yang berulangkali saya sadari ketika melakukan lawatan keliling nusantara dalam rombongan bersama Presiden Sukarno,” ujar ibu dari dua putri dan seorang putra itu.
Ia menimpali, “Keterbelakangan sekian daerah di Indonesia mengharuskan kita membuat reportase menggunakan hati nurani. Dengan kegemaran merekam setiap kali terlihat satu contoh sikap di dalam masyarakat, dan memegang teguh prinsip-prinsip moral dan etik, wartawan akan merebut kepercayaan pembacanya, membesarkan tempatnya bekerja, dan malah mencetak nama bagi dirinya sendiri.”
Khusus mengenai jurnalisme dan perempuan, Herawati menilai ada kesalahan dalam mengembangkan jurnalisme.
“Salah satu kesalahan itu adalah pengucilan berita-berita penting bagi umat manusia sebagai sekadar berita wanita. Berarti itu tidak dianggap penting. Padahal, sebenarnya menyangkut lebih dari separuh penduduk dunia. Persoalan wanita adalah persoalan setengah dunia, bukan persoalan sekelompok kecil masyarakat.”
Herawati sempat menyatakan, “Kini meningkatnya jumlah wartawati di dunia pers membesarkan hati saya. Saya yakin bahwa banyak wanita sependapat dengan saya bahwa wanita dalam posisi lebih baik untuk memperjuangkan nasib sesamanya daripada rekannya yang laki-laki.
Ia menambahkan, “Sebab masih saja terdapat ketiadaan keadilan bagi wanita di pelbagai sektor kehidupan di bumi Indonesia yang tercinta ini. Keuntungan yang kita peroleh sebagai wartawan wanita tidak terhitung banyaknya.”
Herawati juga mendampingi suaminya yang diangkat sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di Cekoslowakia, kemudian Inggris dan terakhir Thailand dalam periode 1959 hingga 1968.
Selepas dari Bangkok, Thailand, kembali ke Jakarta, Herawati menjadi sebagai isteri menteri penerangan karena BM Diah ikut duduk dalam kabinet terakhir Bung Karno (1968). Surat kabar Merdeka dan Indonesian Observer terus terbit selama pengembaraannya, karena Herawati tetap dapat mempublikasikan kesan-kesannya sebagai pemberitaan.
Hingga akhir hayatnya, ia pun tetap rajin menulis dan membaca media massa berbahasa Indonesia maupun asing, bahkan menulis sejumlah buku dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
“Biar tidak cepat pikun,” demikian Herawati Diah, yang juga penerima Bintang Mahaputra pada 1978.
Kini pejuang pers Herawati Diah sudah tiada. Ia meninggal dunia pada usia 99 tahun, Jumat (30/9/2016), pukul 04.20 WIB, di Rumah Sakit Medistra, Jakarta.
Sekretaris pribadi yang juga keluarga Herawati Diah, Damayanti, mengatakan, almarhumah Herawati dirawat di rumah sakit sejak 29 Agustus 2016.
“Beliau meninggal karena usia yang sudah sepuh. Sedangkan secara medis karena terjadi pengentalan darah,” katanya.
Saat ini, jenazah sudah disemayamkan di rumah duka, Jalan Patra Kuningan No 10, Kuningan, Jakarta Selatan. (AN/KB)